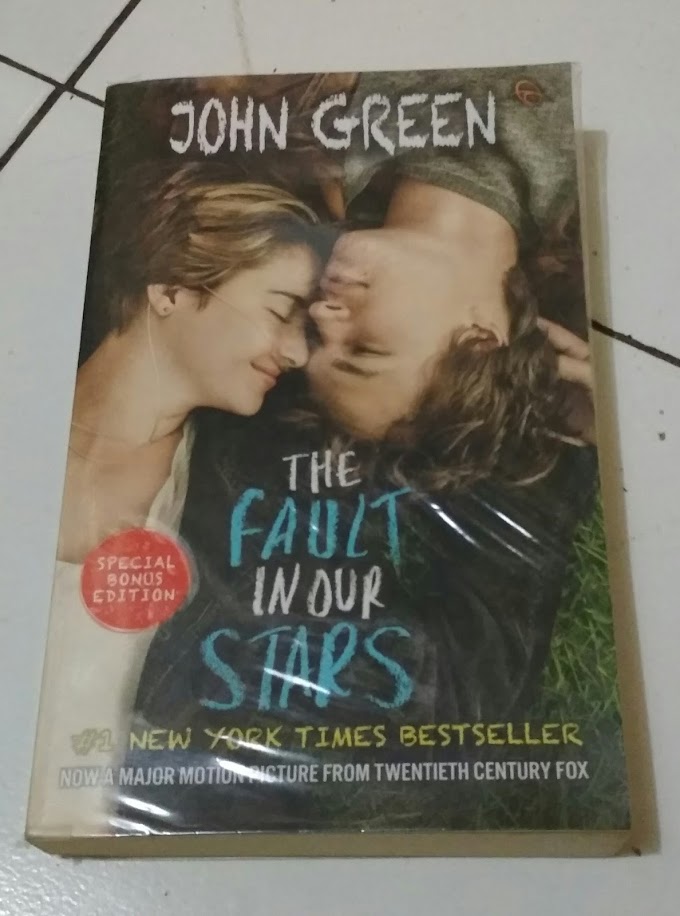Dari SD sampai SMA, nggak banyak rumah teman yang pernah gue kunjungi. Gue memang agak segan main ke rumah teman. Banyak faktor yang membuat gue jarang ke rumah teman. Pertama, gue orangnya kaku. Jangankan ke rumah teman, ke rumah saudara saja gue cuma duduk diam atau menonton televisi. Gue takut kejadian itu juga terjadi di rumah teman. Ditanya orang tuanya teman, gue malah cengengesan nggak nyambung.
Kedua (ini alasan yang dibuat-buat), gue takut nggak bisa pulang lagi. Takut nyasar.
Farhan adalah salah satu teman yang rumahnya pernah gue kunjungi. Waktu itu gue lagi deket banget sama dia. Main ke mana-mana bareng. Dan nggak biasanya, Farhan bisa menjadi teman belajar. Sudah terlalu banyak teman gue yang “diajak main ayo, tapi diajak belajar nolak”. Saat itu, cuma Farhan yang mengerti kondisi kita.
Saat itu gue sedang kelas 6. Persiapan UN lagi getol-getolnya.
Selain jarang ke rumah teman, gue juga agak takut mengajak teman-teman ke rumah. Khawatir mereka nggak suka dengan perlakuan keluarga gue. Takut kalau nantinya keburukan keluarga gue mereka ketahui. Takut keluarga atau rumah gue diomongin di belakang. Gue nggak ngerti kenapa sejak dulu gue selalu ingin dilihat sempurna. Padahal sudah menjadi kodratnya bahwa manusia punya kekurangan.
Mama sering bilang, “Kok teman-temanmu nggak pernah main ke sini?” Gue cuma jawab, “Nggak tahu.” Padahal memang karena gue yang nggak pernah mengundang mereka.
Sampai gue kepikiran, andai suatu saat nanti teman-teman gue menikah, mereka akan memberikan undangan kepada gue. Tetapi mereka nggak menemukan alamat gue karena mereka nggak pernah tahu rumah gue. Karena nggak dapat undangan, gue menyesal nggak bisa datang di acara penuh kebahagiaan teman gue.
Lagi-lagi tidak berlaku pada Farhan. Gue cukup yakin kalau Farhan anaknya nggak suka ngomongin orang lain. Gue percaya dia memang sahabat gue, sampai kapan pun.
Siang itu gue menempati musala mes yang gue jadikan tempat belajar. Gue dan Farhan duduk menghadap papan tulis kecil milik gue. Kakak gue mengajari Matematika, pelajaran kesukaan Farhan.
Tetangga gue melihat kami belajar. “Kamu anak Manyar, ya?” tanyanya kepada Farhan.
Farhan menjawab, “Iya.”
“Kamu tinggal di Manyar, sebelah mananya?”
“Dekat pabrik bihun.”
Mama gue mendengar percakapan tersebut, “Jangan-jangan, kamu anaknya Bu Anu (menyebutkan nama ibunya Farhan). Iya?”
“Iya benar.”
Di luar dugaan, Mama kenal dengan ibunya Farhan. Mereka adalah teman mengaji dan mengenal cukup dekat. Di suatu malam, Mama bilang ke gue, “Mamanya Farhan itu temen baik Mama. Sering curhat-curhatan. Nggak nyangka ya, bisa ketemu begini. Mama sama anaknya temenan baik.”
Gue tersenyum.
Setelah UN, entah dalam kegiatan apa di sekolah—gue lupa, gue menyempatkan ke rumah Farhan. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolah. Di rumah Farhan, gue nontonin Farhan main game Bully. Game yang sangat asing tapi gue sering dengar namanya. Di layar televisi ada seorang anak sekolahan main skateboard di jalan raya. Lalu, dia ngeluarin ketapel. Gue bingung ini mainan apa sebenarnya.
“Mau ke sekolah jam berapa?” tanya gue.
“Nanti aja jam 10,” jawab Farhan.
Farhan kembali memainkan stik kontrolernya.
Mamanya Farhan datang menghampiri gue. “Mau berangkat jam berapa?”
“Kata Farhan jam 10.”
“Oh yaudah. Mama Farhan pamit dulu, ya.”
Gue mencium punggung tangan beliau.
Singkatnya, kami satu sekolah lagi di SMP. Namun kami tidak seakrab dulu karena Farhan telah masuk ke dunia “game”. Setiap hari kerjaannya main Point Blank di warnet terus. Gue, karena nggak punya pegangan hidup saat itu, ikut-ikutan menjadi anak warnet, minimal hari Sabtu gue main Point Blank selama lima jam.
Setelah uang gue terhambur banyak, gue menyadari bahwa gue nggak cocok jadi gamers. Dan gue punya pandangan sinis terhadap gamers.
Karena itu mungkin, gue agak jauh darinya. Farhan bukanlah orang yang gue kenal seperti saat SD dulu. Tapi gue nggak putus hubungan dengan dia. Farhan tetaplah sahabat. Meskipun gue yang memutuskan menjauh darinya. Lebih tepatnya, karena kebiasaannyalah yang membuat gue jauh darinya.
Terakhir kali ketemu Farhan saat buka puasa bersama tahun ini. Teman-teman seangkatan SMP berkumpul di sana. Gue berharap teman-teman yang dekat dengan gue datang. Untungnya Farhan datang. Gue cerita banya tentang kehidupan sekolah.
“Gue nggak tahu deh, kalau nggak karena nilai kasihan dari guru, nasib gue udah kayak gimana,” ujar gue.
“Apalagi gue, Bi. Belajar aja nggak pernah.”
Kemudian kita tertawa. Kita saling menertawai nasib di SMA yang kehidupannya lebih keras daripada di SMP. Tawa yang gue rindukan.
Suatu malam dalam perjalanan pulang dari minimarket, gue melihat Farhan di pinggir jalan raya. Dia duduk di atas motor memainkan handphone-nya. Raut wajahnya terlihat seperti menunggu seseorang. Gue hendak memanggil, tetapi sadar bahwa kondisi jalan sedang macet, nggak mungkin gue teriak. Bisa-bisa digetok pengendara motor. Gue lanjut mengayuh sepeda.
Enam tahun gue tidak pernah mengunjungi rumahnya, malam Minggu kemarin gue ke rumahnya. Tiga minggu setelah gue gagal menyapanya.
Gue memarkirkan sepeda fixie merah di depan rumahnya. Ada dua orang bapak yang sedang duduk di kursi hijau.
“Bi.”
“Bi.”
“Bi.”
Tiga panggilan itu membuat gue menoleh ke belakang. Ada Farhan di sana, di depan gerbang kayu rumahnya.
Rumah yang enam tahun tidak gue kunjungi, kini lebih ramai. Nggak banyak perubahan dari susunannya. Warna dinding dengan cat krem masih dipertahankan. Tanaman di sampinya pun masih sama. Mungkin ada satu-dua perubahan di sana.
Farhan tatapannya beda. Tidak seperti Farhan yang biasanya. Tidak seperti Farhan ketika antusias mengerjakan soal Matematika dulu. Tidak seperti Farhan yang gue kenal.
Tatapannya nggak ceria.
“Mama lu udah tahu?” tanyanya.
Gue menangguk.
“Ya udah, masuk. Yang lain udah di dalam.”
Gue duduk di teras rumah Farhan. Ada dua teman SMP di sana. Kacang dihidangkan di atas piring. Orang-orang, yang nampaknya saudara Farhan, membawa tumpukan buku Yasin.
Gue di sini, tidak untuk menonton Farhan main Bully.
Melainkan,
hadir dalam acara tiga harian meninggalnya ibunya Farhan.
Kata terakhir yang pernah gue dengar “Mama Farhan pamit dulu, ya” menjadi kata terakhir, sekaligus kata yang benar-benar menggambarkan keadaan sekarang. Beliau benar-benar pamit. Meskipun nggak mengenal begitu dekat, gue jelas sedih mendengar meninggalnya beliau. Apalagi Mama yang sudah menganggapnya sebagai sahabat.
Pasca datang ke rumah Farhan, gue kembali takut.
Takut.
Takut.
Benar-benar takut.
Gue takut akan kenyataan, bahwa kita memang nggak akan selamanya di dunia ini.
Apa pun yang kita miliki rasanya sangat berharga bila ditinggalkan begitu saja. Teman-teman, saudara, sahabat, guru-guru akan kita tinggalkan kelak. Betapa nikmatnya kehidupan di dunia ini membuat gue terlena, hingga lupa bahwa kita akan berakhir dengan kematian. Ambisi, kecewa, bahagia, dan semuanya menutupi kenyataan yang ada.
Kematian memang ada.
Nonton video, baca novel kesukaan, mengerjakan soal-soal hingga tengah malam seperti menjadi tipuan yang kita buat sendiri untuk menghilangkan kenyataan itu. Kenyataan yang kalau kita ingat secara artian lain membuat kita segan untuk merasa hidup.
Gue jadi mikir, bagaimana bila nanti nggak mendapat tempat terbaik di alam akhirat nanti, seperti yang telah dijanjikan-Nya?
Mungkin aku tak pantas menjadi penghuni Surga Firdaus. Namun, aku tidak kuat dengan panasnya api Neraka Jahim.
Terjemahan dari salawat yang akhir-akhir ini sering gue baca menggambarkan keadaan jiwa saat ini. Surga tempat yang tak pantas bagi pendosa seperti gue, tetapi tak sanggup bila ditempatkan di neraka-Nya.
Kemudian gue menemukan titik terang. Manusia memang tempatnya salah dan dosa tak dapat dihindarkan. Perbanyak amal ibadah adalah salah satu cara mengimbangi ketimpangan itu.
Ada perkataan yang berbunyi seperti ini: “Orang yang cerdas adalah orang yang senatiasa mengingat kematian.”
Sebelum ruh tak lagi bersama badan, marilah kita perbanyak amal ibadah dalam rangka menutup akhir tahun. Jadikan momen akhir tahun ini sebagai media perenungan apa saja yang telah kita perbuat sepanjang tahun.
Kedua (ini alasan yang dibuat-buat), gue takut nggak bisa pulang lagi. Takut nyasar.
Farhan adalah salah satu teman yang rumahnya pernah gue kunjungi. Waktu itu gue lagi deket banget sama dia. Main ke mana-mana bareng. Dan nggak biasanya, Farhan bisa menjadi teman belajar. Sudah terlalu banyak teman gue yang “diajak main ayo, tapi diajak belajar nolak”. Saat itu, cuma Farhan yang mengerti kondisi kita.
Saat itu gue sedang kelas 6. Persiapan UN lagi getol-getolnya.
Selain jarang ke rumah teman, gue juga agak takut mengajak teman-teman ke rumah. Khawatir mereka nggak suka dengan perlakuan keluarga gue. Takut kalau nantinya keburukan keluarga gue mereka ketahui. Takut keluarga atau rumah gue diomongin di belakang. Gue nggak ngerti kenapa sejak dulu gue selalu ingin dilihat sempurna. Padahal sudah menjadi kodratnya bahwa manusia punya kekurangan.
Mama sering bilang, “Kok teman-temanmu nggak pernah main ke sini?” Gue cuma jawab, “Nggak tahu.” Padahal memang karena gue yang nggak pernah mengundang mereka.
Sampai gue kepikiran, andai suatu saat nanti teman-teman gue menikah, mereka akan memberikan undangan kepada gue. Tetapi mereka nggak menemukan alamat gue karena mereka nggak pernah tahu rumah gue. Karena nggak dapat undangan, gue menyesal nggak bisa datang di acara penuh kebahagiaan teman gue.
Lagi-lagi tidak berlaku pada Farhan. Gue cukup yakin kalau Farhan anaknya nggak suka ngomongin orang lain. Gue percaya dia memang sahabat gue, sampai kapan pun.
Siang itu gue menempati musala mes yang gue jadikan tempat belajar. Gue dan Farhan duduk menghadap papan tulis kecil milik gue. Kakak gue mengajari Matematika, pelajaran kesukaan Farhan.
Tetangga gue melihat kami belajar. “Kamu anak Manyar, ya?” tanyanya kepada Farhan.
Farhan menjawab, “Iya.”
“Kamu tinggal di Manyar, sebelah mananya?”
“Dekat pabrik bihun.”
Mama gue mendengar percakapan tersebut, “Jangan-jangan, kamu anaknya Bu Anu (menyebutkan nama ibunya Farhan). Iya?”
“Iya benar.”
Di luar dugaan, Mama kenal dengan ibunya Farhan. Mereka adalah teman mengaji dan mengenal cukup dekat. Di suatu malam, Mama bilang ke gue, “Mamanya Farhan itu temen baik Mama. Sering curhat-curhatan. Nggak nyangka ya, bisa ketemu begini. Mama sama anaknya temenan baik.”
Gue tersenyum.
***
Setelah UN, entah dalam kegiatan apa di sekolah—gue lupa, gue menyempatkan ke rumah Farhan. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolah. Di rumah Farhan, gue nontonin Farhan main game Bully. Game yang sangat asing tapi gue sering dengar namanya. Di layar televisi ada seorang anak sekolahan main skateboard di jalan raya. Lalu, dia ngeluarin ketapel. Gue bingung ini mainan apa sebenarnya.
“Mau ke sekolah jam berapa?” tanya gue.
“Nanti aja jam 10,” jawab Farhan.
Farhan kembali memainkan stik kontrolernya.
Mamanya Farhan datang menghampiri gue. “Mau berangkat jam berapa?”
“Kata Farhan jam 10.”
“Oh yaudah. Mama Farhan pamit dulu, ya.”
Gue mencium punggung tangan beliau.
Singkatnya, kami satu sekolah lagi di SMP. Namun kami tidak seakrab dulu karena Farhan telah masuk ke dunia “game”. Setiap hari kerjaannya main Point Blank di warnet terus. Gue, karena nggak punya pegangan hidup saat itu, ikut-ikutan menjadi anak warnet, minimal hari Sabtu gue main Point Blank selama lima jam.
Setelah uang gue terhambur banyak, gue menyadari bahwa gue nggak cocok jadi gamers. Dan gue punya pandangan sinis terhadap gamers.
Karena itu mungkin, gue agak jauh darinya. Farhan bukanlah orang yang gue kenal seperti saat SD dulu. Tapi gue nggak putus hubungan dengan dia. Farhan tetaplah sahabat. Meskipun gue yang memutuskan menjauh darinya. Lebih tepatnya, karena kebiasaannyalah yang membuat gue jauh darinya.
***
Terakhir kali ketemu Farhan saat buka puasa bersama tahun ini. Teman-teman seangkatan SMP berkumpul di sana. Gue berharap teman-teman yang dekat dengan gue datang. Untungnya Farhan datang. Gue cerita banya tentang kehidupan sekolah.
“Gue nggak tahu deh, kalau nggak karena nilai kasihan dari guru, nasib gue udah kayak gimana,” ujar gue.
“Apalagi gue, Bi. Belajar aja nggak pernah.”
Kemudian kita tertawa. Kita saling menertawai nasib di SMA yang kehidupannya lebih keras daripada di SMP. Tawa yang gue rindukan.
Suatu malam dalam perjalanan pulang dari minimarket, gue melihat Farhan di pinggir jalan raya. Dia duduk di atas motor memainkan handphone-nya. Raut wajahnya terlihat seperti menunggu seseorang. Gue hendak memanggil, tetapi sadar bahwa kondisi jalan sedang macet, nggak mungkin gue teriak. Bisa-bisa digetok pengendara motor. Gue lanjut mengayuh sepeda.
Enam tahun gue tidak pernah mengunjungi rumahnya, malam Minggu kemarin gue ke rumahnya. Tiga minggu setelah gue gagal menyapanya.
Gue memarkirkan sepeda fixie merah di depan rumahnya. Ada dua orang bapak yang sedang duduk di kursi hijau.
“Bi.”
“Bi.”
“Bi.”
Tiga panggilan itu membuat gue menoleh ke belakang. Ada Farhan di sana, di depan gerbang kayu rumahnya.
Rumah yang enam tahun tidak gue kunjungi, kini lebih ramai. Nggak banyak perubahan dari susunannya. Warna dinding dengan cat krem masih dipertahankan. Tanaman di sampinya pun masih sama. Mungkin ada satu-dua perubahan di sana.
Farhan tatapannya beda. Tidak seperti Farhan yang biasanya. Tidak seperti Farhan ketika antusias mengerjakan soal Matematika dulu. Tidak seperti Farhan yang gue kenal.
Tatapannya nggak ceria.
“Mama lu udah tahu?” tanyanya.
Gue menangguk.
“Ya udah, masuk. Yang lain udah di dalam.”
Gue duduk di teras rumah Farhan. Ada dua teman SMP di sana. Kacang dihidangkan di atas piring. Orang-orang, yang nampaknya saudara Farhan, membawa tumpukan buku Yasin.
Gue di sini, tidak untuk menonton Farhan main Bully.
Melainkan,
hadir dalam acara tiga harian meninggalnya ibunya Farhan.
Kata terakhir yang pernah gue dengar “Mama Farhan pamit dulu, ya” menjadi kata terakhir, sekaligus kata yang benar-benar menggambarkan keadaan sekarang. Beliau benar-benar pamit. Meskipun nggak mengenal begitu dekat, gue jelas sedih mendengar meninggalnya beliau. Apalagi Mama yang sudah menganggapnya sebagai sahabat.
***
Pasca datang ke rumah Farhan, gue kembali takut.
Takut.
Takut.
Benar-benar takut.
Gue takut akan kenyataan, bahwa kita memang nggak akan selamanya di dunia ini.
Apa pun yang kita miliki rasanya sangat berharga bila ditinggalkan begitu saja. Teman-teman, saudara, sahabat, guru-guru akan kita tinggalkan kelak. Betapa nikmatnya kehidupan di dunia ini membuat gue terlena, hingga lupa bahwa kita akan berakhir dengan kematian. Ambisi, kecewa, bahagia, dan semuanya menutupi kenyataan yang ada.
Kematian memang ada.
Nonton video, baca novel kesukaan, mengerjakan soal-soal hingga tengah malam seperti menjadi tipuan yang kita buat sendiri untuk menghilangkan kenyataan itu. Kenyataan yang kalau kita ingat secara artian lain membuat kita segan untuk merasa hidup.
Gue jadi mikir, bagaimana bila nanti nggak mendapat tempat terbaik di alam akhirat nanti, seperti yang telah dijanjikan-Nya?
Mungkin aku tak pantas menjadi penghuni Surga Firdaus. Namun, aku tidak kuat dengan panasnya api Neraka Jahim.
Terjemahan dari salawat yang akhir-akhir ini sering gue baca menggambarkan keadaan jiwa saat ini. Surga tempat yang tak pantas bagi pendosa seperti gue, tetapi tak sanggup bila ditempatkan di neraka-Nya.
Kemudian gue menemukan titik terang. Manusia memang tempatnya salah dan dosa tak dapat dihindarkan. Perbanyak amal ibadah adalah salah satu cara mengimbangi ketimpangan itu.
Ada perkataan yang berbunyi seperti ini: “Orang yang cerdas adalah orang yang senatiasa mengingat kematian.”
Sebelum ruh tak lagi bersama badan, marilah kita perbanyak amal ibadah dalam rangka menutup akhir tahun. Jadikan momen akhir tahun ini sebagai media perenungan apa saja yang telah kita perbuat sepanjang tahun.