Tinggal berdua dalam satu rumah adalah hal yang tidak pernah aku inginkan. Apakah ada lelaki, berumur enam belas tahun, yang menginginkan tinggal bersama adiknya, yang baru berumur delapan bulan? Agak gila. Aku seperti gadis belasan tahun yang disetubuhi hingga hamil kemudian ditinggal sang lelaki bajingan.
Aku seringkali membuat penyangkalan, bahwa aku tidak pantas ditempatkan dalam kondisi begini. Tinggal serumah dengan manusia yang tidak bisa membantuku mengerjakan apa pun. Aku seperti hidup sendiri, kemudian diberi beban lagi. Saat diri tidak terkontrol, sepintas aku berpikir ingin menusuk pisau roti ke punggung adikku, sehingga beban di rumah ini berkurang.
Ayahku pergi dua bulan sebelum Herman, adikku, dilahirkan. Ibuku tak kuketahui kabarnya pasca-melahirkan. Aku tak pernah mendapatkan informasi pasti di mana keberadaan kedua orang tuaku. Kerabat terdekatku, Tante Tresna, mengatakan, mereka ada di sebuah kota untuk mencari nafkah, dan kedua anaknya dititipkan pada adik Ayah tersebut.
Hanya bertahan lima bulan Tante Tresna menampung kami. Lamaran pekerjaannya di salah satu bank swasta diterima. Setelahnya, beginilah kondisi keluarga kami: hilang arah tanpa ada nakhoda di dalamnya—yang biasa kami sebut orang tua.
Membagi waktu antara belajar, merawat adik, dan bekerja sangatlah menyusahkan. Jujur saja aku kepayahan menjalaninya. Seperti sore ini, aku sedang menyiapkan bumbu untuk berjualan nasi goreng sambil menjaga adikku. Bahan-bahan yang sudah kubeli siap dihaluskan. Namun, pisau yang biasa kuletakkan di atas meja makan kini tidak pada tempatnya.
“Kulkas.”
Suara itu spontan terdengar. Aku kaget. Siapa yang berkata tadi? Yang ada di rumahku hanyalah aku dan adik. Mustahil Herman yang bicara.
Mungkin suara itu bisa jadi petunjuk. Aku pernah menonton serial kartun Dora The Explorer di televisi. Saat Dora mengajak penontonnya di rumah berinteraksi, aku memberi tahu ke mana dia harus pergi. Padahal, di luar sana, si Dora sialan pasti tidak mendengarku. Akhirnya, dia pergi ke tempat yang aku sebutkan.
Aku mengikuti apa kata suara asing tersebut, seperti Dora mengikuti perintahku.
Aku membuka kulkas. Seketika aku merasa bodoh tidak mendapatkan pisau di sana.
“Atas.” Suara asing itu muncul lagi sama persis. Aku melirik ke adik, dia merangkak sambil menunjuk-nunjuk ke atas kulkas. Aku semakin bingung karena dia sebelumnya belum bisa bicara. Kata pertama yang dia ucap justru kulkas. Seharusnya, kata pertama yang diucap seorang bayi adalah “ibu” atau “ayah”, bukannya kulkas. Atau memang kulkas dia anggap sebagai orang tuanya?
“Atas?” Aku melihat ke atas kulkas dan medapatkan pisau yang kuinginkan. Memotong cabai dan meracik bumbu nasi goreng yang pernah Ibu ajarkan.
Sebelum berangkat sekolah, sepucuk amplop putih diantarkan tetanggaku. Kemarin sore surat ini sampai kepadanya dan dia lupa menyampaikan padaku. Aku membacanya pada jam istirahat pertama di sekolah.
Jati, semoga kamu baik-baik saja. Ini Ibu. Maaf belum bisa berkunjung sampai penghujung tahun berakhir. Kamu belajar yang giat, ya. Ibu janji, saat kita bertemu nanti, Ibu akan memelukmu erat. Kamu harus sekuat pohon jati, itulah filosofi yang diberikan untuk namamu.
Salam sayang,
Ibu.
Surat itu tak begitu berkesan ketika membacanya kali pertama. Sampai di tempat berjualan, di bawah lampu petromaks, aku membaca surat itu. Walau hanya kertas biasa, aku bisa mencium aroma yang tak biasa.
Aroma kerinduan.
Kudekap surat itu. Ibu, aku rindu.
***
Seminggu lagi akan ada Ujian Akhir Semester. Aku mulai mengurangi jam berjualan agar bisa menyisihkan waktu untuk belajar, mengejar materi yang belum mampu aku kuasai. Aku menyadari bahwa akan sangat menyulitkan bila belajar sendiri. Aku membutuhkan pembimbing untuk mengajariku. Aulia, teman sekelasku, membolehkan aku belajar di rumahnya. Kebetulan rumahnya dekat dari tempatku berjualan.
“Jati, mau coba nasi goreng kamu dong.”
“Boleh. Bayar ya.” ucapku setengah bercanda.
“Boleh. Tapi kamu bayar aku juga.”
Aku dan Aulia tertawa.
Setelah selesai belajar, aku melanjutkan berjualan pukul 9 malam. Aku sudah berencana sekitar pukul 12 aku pulang.
“Kok baru datang?” tanya satpam kompleks.
“Biasa, Pak. Habis pacaran dulu tadi,” kataku bercanda.
“Yeh. Kerja dulu yang bener. Kalau udah kaya, baru deh nikah sama anak gue!” Pak Satpam kemudian tertawa.
“Anak bapak cewek, kan?”
“Bukan. Anak gue burung beo!” katanya kesal. “Ya, cewek lah. Nanti gue kenalin deh. Tapi umurnya baru dua tahun.”
Pak Satpam memang sering bercanda denganku. Aku sudah menganggapnya seperti Ayah, yang entah bagaimana rasanya memiliki Ayah seperti apa. Tapi, Pak Satpam punya karisma yang sanggup menggantikan sosok Ayah.
***
Pagi hari sebelum berangkat sekolah, aku kembali mendapat surat.
Jati, hari ini adalah hari pertama kamu UAS. Ibu harap, kamu bisa mengerjakan soal-soal dengan tenang. Tanpa beban pikiran. Percayalah pada Ibu, kamu bisa mendapat nilai bagus. Jangan lupa mengulang pelajaran yang pernah diajarkan di sekolah. Kamu ingat bulan ini ada Hari Ibu? Ibu harap, Ibu bisa bertemu kamu.Surat yang justru membuatku tak kuasa menahan tangis di hadapan lembar soal ujian. Aku berulang kali meminta kertas baru kepada pengawas karena tetesan air mataku membasahi kertas. Soal-soal Matematika menjadi terasa sangat sulit.
Salam rindu,
Ibu
Ibu, kenapa kau datang membawa kesulitan padaku hari ini? Tapi, aku tetap rindu Ibu.
Semenjak surat itu datang aku tidak pernah konsentrasi mengerjakan apa pun. Aku berhenti berjualan untuk sementara waktu sampai kondisi jiwaku benar-benar stabil. Beberapa kali aku kehilangan keseimbangan. Aku hampir jatuh di jalan karena merasakan pusing yang hebat. Genggaman tanganku, tidak biasanya, menjadi lemah. Lima kali aku menjatuhkan piring dan gelas dalam sehari di rumah.
Saat ini yang kubutuhkan adalah orang yang paling dekat hubungannya denganku. Tetangga memang dekat dari rumah, tapi tidak cukup dekat bila kuceritakan apa saja yang terjadi pada diriku.
UAS selesai dengan banyak sekali kesalahan yang kubuat. Beberapa hafalan dan rumus tiba-tiba memusuhi diriku. Suara lembar soal yang dibuka terdengar mengejekku karena gagal menjawabnya.
Masa-masa seperti ini yang membuatku ingin mengakhiri hidup secepatnya.
Aulia nampaknya khawatir dengan kekacauan yang terjadi pada diriku. “Kamu beda dari biasanya, Jati. Ada masalah?”
“Sedikit.”
“Aku nggak maksa kamu buat cerita.” Aulia mengambil sebuah wafer yang tergeletak di meja kantin. “Mau wafer?”
Aku mengambil dua buah wafer. Mengambil selapis demi selapis untuk dijilati krimnya. Sekolah semakin sepi. Pedagang di kantin mulai memberesi dagangannya.
“Kamu nggak jualan hari ini?”
“Nggak bergairah untuk saat ini. Entahlah,” kataku. “Sepertinya semua kebiasaan yang sudah kubangun sejak tiga bulan terakhir runtuh karena sesuatu.”
***
Aku datang ke depan kompleks, tetapi tidak mendorong gerobak. Aku datang tidak untuk berjualan.
“Mana gerobak lu?” tanya Pak Satpam.
“Nggak jualan dulu, Bos. Hehehe.”
“Terus mau apa ke sini?”
“Berani tanding catur?” ajakku.
“Ayo.”
Semalaman suntuk aku bermain catur dengan Pak Satpam. Tanpa henti hingga bergelas-gelas kopi dan berbutir-buti kacang jatuh ke tenggorokan. Aku benar-benar melepas semua ketegangan yang ada di kepalaku. Aku tak peduli besok ada jadwal sekolah. Aku percaya besok sudah tidak ada kegiatan karena UAS telah selesai.
“Lo tau nggak, Boy? Waktu gue sebesar lo, gue bego banget main catur,” katanya memulai cerita.
“Masa, sih?”
“Menurut gue, raja tuh sebenernya goblok. Nggak bisa apa-apa. Maunya dilindungi doang. Gue malah lebih suka ratu, karena... gue cowok! Ratu kan cewek, gue cowok. Pas!”
Ucapannya mulai aneh. Aku mulai takut dia akan membeberkan rahasia celana dalam istrinya.
Aku tertidur di pos satpam kompleks. Terbangun pada waktu yang tepat saat muazin mengetukkan jari di mikrofon. Jalan sempoyongan setengah sadar saat azan Subuh berkumandang, aku ke masjid untuk menyegarkan diri berwudu dan salat berjamaah. Selesai salat aku kembali tertidur hingga matahari tepat di atas ubun-ubun.
Herman, seperti biasanya, tidak ada di rumah. Dia sedang tidur siang di rumah tetangga. Sejak aku bekerja dia memang aku titipi, kecuali pada hari-hari tertentu saat aku butuh dia untuk menemani di rumah. Aku ingin mengetahui kondisinya dan segera ke rumah tetangga.
“Titipan surat lagi,” kata tetanggaku menyerahkan amplop putih.
“Oh iya? Ada uangnya nggak, Bu?” ledekku.
“Nggak tahu deh. Saya nggak sempat ngintip.”
Aku menggendong pulang Herman yang tertidur pulas dan sepucuk amplop putih.
Jati, tanggal 22 Desember nanti hari pembagian rapor, bukan? Maaf, Ibu tidak bisa mengambilnya, begitu pun ayah. Kamu ambil sendiri saja, ya. Atau bisa meminta bantuan tetangga. Kabar baiknya, Ibu akan menemui kamu sore harinya. Ibu janji. Sore hari, kamu temui Ibu di pasar besar kota seberang. Ibu harap, kamu tidak lupa Hari Ibu.
Semoga nilaimu baik semester ini.
Saat pembagian rapor, tidak ada pilihan lain, aku mengambilnya sendiri. Herman aku titipkan di rumah tetangga. Dengan begitu aku tidak akan mengurusi dia dalam kemampuanku merawat bayi yang teramat payah ini.
Wali kelasku menanyakan tentang orang tuaku. “Kamu kenapa ambil rapor sendiri?” tanyanya. Aku setengah tertunduk menjawabnya, “Saya nggak tahu orang tua saya di mana, Bu.” Aku juga menjelaskan tentang pekerjaanku, supaya aku bisa sedikit membela bila nilaiku buruk dengan alasan sibuk bekerja.
Aku sebenarnya agak takut bila Ibu Arafah, wali kelasku, akan marah karena rapor tidak diambil orang tua. Namun, dia memberi pemakluman dengan alasan yang kuberi tadi. Dia hanya memberi sedikit nasihat dan motivasi belajar kepadaku.
***
Dengan menaiki angkot, aku menuju pasar yang dimaksud di dalam surat itu. Aku tidak membawa apa-apa untuk pertemuan ini: pertemuan yang sudah kurindukan sejak sembilan bulan yang lalu.
Sampai di sana, pasar cukup sepi, bahkan tempat ini tidak layak disebut pasar karena pasar identik dengan keramaian. Sambil menunggu Ibu aku minum es dawet di depan bank yang berada di tengah-tengah pasar. Di seberang jalan, mobil merah berhenti. Turun seorang wanita mengenakan kerudung biru dongker dipadukan gamis dengan warna senada. Dia menoleh ke kanan dan kiri, kemudian melihatku. Dia berjalan mendatangi aku.
“Jati?”
“Iya. Ibu?” tanyaku, setengah ragu.
“Benar, Jati.”
Aku tak sanggup menahan semuanya. Aku langsung memeluk Ibu erat-erat. Dia juga memelukku. Dari sudut matanya mengalir sungai kecil di pipinya. “Aku yang sering mengirim surat untuk kamu.”
Aku tak peduli lagi apa perkataannya, yang penting aku bisa bersamanya. Namun, aku menyadari ada hal berbeda dari wanita yang sedang kupeluk erat ini.
“Jati, kamu harus dengar ini.”
Aku dan Ibu duduk di bangku pinggir jalan.
“Sebenarnya,” kata Ibu menatap wajahku, “aku ibu yang lain dari ayahmu. Aku ibu tirimu.”
Kaget. Denyut nadiku perlahan melambat mendengar perkataan dia.
“Aku ibu tirimu. Ayah kamu menikahi aku dua bulan sebelum ibu kamu melahirkan. Ayah kamu akhirnya nggak sanggup membayar biaya rumah sakit karena uang yang dia miliki habis untuk menikah denganku.”
“DASAR WANITA BA—“
“Tunggu dulu.” Dia menunda luapan amarahku. “Kamu tidak sepenuhnya kehilangan ibumu.”
“Cepat! Tolong pertemukan aku dengan ibuku. Kamu bukan ibuku!”
Dia mengajakku menelusuri isi pasar. “Ibu kamu ada di sini.”
Beberapa kios sayur kami lewati. Aroma bumbu rendang tercium dari kejauhan. Bunyi bising pemarut kelapa terdengar. Namun, di mana ibu sebenarnya?
Ibu tiriku membuka pintu kayu yang digembok. Di dalamnya terdapat banyak sekali batok kelapa. Seorang wanita yang kedua kakinya terjepit di antara dua kayu sedang duduk terkulai lemas.
“Itu ibu kamu.”
“Benar? Kenapa ibu ada di sini?” tanyaku tidak percaya.
“Kamu siapa?” katanya sambil menunjuk aku dan ibu tiriku. “Jangan pacaran di sini. Anak saya sekarang sudah jadi Menteri Luar Negeri Portugal! Hahahaha.”
“Ibu kamu jiwanya terganggu, Jati. Sejak ditinggal ayah dan melahirkan, dia jadi murung. Dia nggak kembali lagi ke rumah setelah keluar dari rumah sakit.”
“Ibu....” Aku menjerit dan memeluk Ibu. “Ibu, maafin Jati ya, kalau selama ini Jati banyak dosa sama Ibu. Aku kesepian tanpa Ibu. Herman juga. Ibu jangan begini, Bu.”
Aku mengeluarkan rapor dan memberi tahu Ibu. “Bu, aku nggak bisa kasih apa-apa. Tapi, aku ranking satu di kelas, Bu.”
“Makasih telah melahirkan Jati, Bu. Aku sayang Ibu. Selamat Hari Ibu.”
--
Sumber gambar: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/envelope-vector-488529
Tulisan ini diikutsertakan dalam giveaway blognya Yoga Akbar Sholihin bertemakan "Ibu".



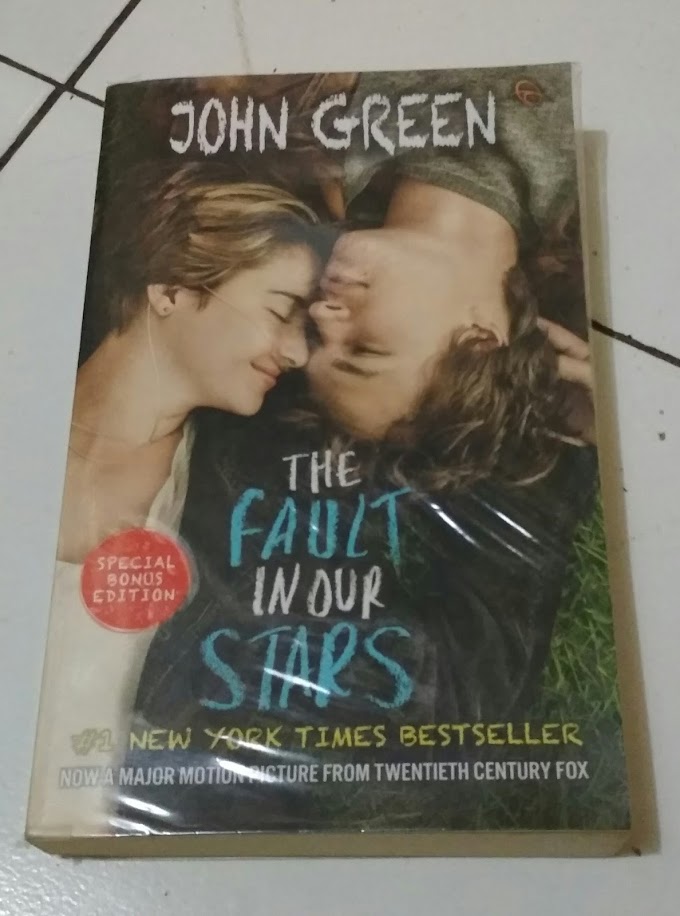




29 Comments
Yg udah buat ibu jati itu begitu adalah penulisnya
ReplyDeletePenulisnya jaat
:(
DeleteKamu harus kuat sesuai namamu JATI
ReplyDeleteSeperti kayu jati yang ada di meja makan.
DeleteKalo menurut gue sih si Jati itu enak hidupnya bedua sama adiknya. Kalo gue yg jadi jati, secara gue cewek yah, jadi di sini jati versi gue ya jati yang kelaminnya cewek, hmm...waaaaa gilaaaaa gue yg ngatur rumah sendiri..itu asik dan cewek kan biasanya lebih gampang dapet kerjaan daripada cowok.. (tanpa bermaksud menyinggung lho). Hahahah... ya kali hidup sesederhana itu yah..
ReplyDeleteHuahaha, tapi cewek nggak bisa jadi office boy, lho.. :p
DeleteGue malah kasian sama herman. Untungnya ada tetangga yang baik. :'))
ReplyDeleteSemoga menang, Rob. Kalo gak menang,pasti ada orang dalem yang ngacauin penilaiannya :))
Eh gimana? Orang dalem lagi yang ngacau? Aamiin Ya Allah.
Deleteibu :(
ReplyDeleteAyah... :(
DeleteAdik kecilku ini paling jago kalau bikin cerpen. HUaaa. Dasar Robby ba...
ReplyDeleteIni sedih. Nggak nyangka yang ngirimin surat itu sebenarnya ibu tirinya. Dan walaupun sedih, aku sempat ngakak di beberapa bagian. Mesum anjir! Aulia sempat minta dibayar segala lah. Trus Menteri Negara Portugal apaan. Ngahahaha. Bangke bener si Robby Masterchev.
DUKUNG ROBBY MENANG GA YOGA!
Jangan panggil itu dong. Haryanchev sudah bagus, karena nggak ada di Google yang pake nama itu. :))
DeleteAamiin. Doain aja dia khilaf. :)
Sedih banget euy :(
ReplyDeleteUntung enggak sambil dengerin lagu Iwan Fals - Sore Tugu Pancoran.
Semoga dapet juara 1 ya cees. Kebangetan pisan lah kalau Yoga Akbar Sholihin gak menangin cerita ini mah.
Belum pernah denger lagu itu, cees. Jadi saya yang lebih sedih karena gak tau lagu itu.
DeleteAamin. Semoga dia khilaf.
Gue baca loh, ini.
DeleteHalo!
DeleteKeren. Secara cerita bagus banget. Moga menang, Rob. Gue ngiler juga mau ikutan~
ReplyDeleteAamiin. Ikutan dong biar rame! :)
Deletejadi... menang gak nih?
ReplyDeletebelom pengumuman nih... pengumuman UN.
Delete:(
ReplyDeleteSialan. Ditipu twist gue. Maaf untuk keputusan ini. Iya, karena baru sempet komentar. Sengaja nunggu deadline abis dulu.
ReplyDeleteKenapa harus Portugal? Kenapa gak Nigeria?
Karena di Portugal ada idolaku. Cristiano Ronaldowati. ^__^
DeleteHuum sungguh ending yang bikin gue tercengang dan sempet salah tebak akan berakhor begitu, gue pikir pas ketemuan di pasar sepi ternyata pasar tersebut kuburan lalu ibunya telah tiada, ternyata ibu si jati telah menjadi gila ya, cukup tragis sih rob...kesian. tapi salut juga tokoh yang diciptain punya tanggung jawab juga mengingat masih sma, trus ngasuh adik kecil n jualan nasi goreng juga
ReplyDeleteAndai aku karakter Jati, Mbak. Pasti aku nggak ngeblog. :')
DeleteGue juga ikutan ni giveawaynya yoga
ReplyDeleteYeaay. Semoga menang, ya, Mbak. Aku belum baca, nih.
DeletePas aku baca tulisan ini, entah kenapa aku malah merasa sebagai seorang jati. Di umur yg semuda itu dia sudah diberi beban hidup yg berat, menghidupi diri sendiri dan adiknya dengan berjualan nasi goreng :')
ReplyDeleteSedih euyy... semoga menang ya rob..
Mas Fan begitu juga? Aduh, iya sedih kalau begitu mah. :((
DeleteAamiin. Semoga menang juga Mas Fan!
Terima kasih sudah membaca. Mari berbagi bersama di kolom komentar.
Emoji