Aku, lelaki berumur setengah abad, sedang menikmati kopi hitam, hanya mengenakan sarung. Duduk di bangku panjang di depan rumah, memperhatikan tetangga yang sedang menyapu. Sesekali teman-temanku lewat menyapa, sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Sedangkan anakku, sudah berangkat 30 menit yang lalu.
Aku mengambil koran di meja kemudian membacanya. Aku lihat tanggal terbitnya, ah, ini koran sebulan yang lalu. Mungkin itu terakhir kalinya aku membeli koran, dan itu terakhir kalinya aku pulang kerja.
Karena, sebulan yang lalu aku dipecat.
Pulang ke rumah dengan langkah gontai, menemui penjual koran langganan. “Mas, ini mungkin terakhir kalinya saya beli koran di tempat, Mas.”
“Memang kenapa, Pak?” tanya penjual koran kepadaku.
“Nggak papa. Mungkin saya akan beli di tempat lain atau membaca berita online. Ini, kan, era digital. Hehehe,” kataku berdalih. Padahal aku samasekali nggak punya handphone.
Aku menyeruput kopi yang mulai mendingin. Ah, rasanya terlalu pahit. Sejak dipecat dari pabrik tempatku berkerja, otomatis kopi yang aku minum terasa pahit. Wajarlah, untuk membeli gula butuh banyak pertimbangan. Lebih baik uangnya dibelikan sebungkus nasi. Tapi tak apa, kopi ini adalah sisa dari persediaan tiga bulan. Memang, aku selalu membeli kopi untuk stok tiga bulan. Biar nggak bolak-balik ke pasar.
Merenung. Mengapa semua terjadi secara mendadak. Di saat keluargaku dalam keadaan baik-baik saja, kenapa pemecatan itu bisa datang? Apakah ini semua adalah balasan dari kebiasaan burukku selama lima tahun terakhir?
Entahlah, tapi aku merasa ini teguran dari Tuhan.
Lima tahun lalu adalah kali pertama aku keluar malam untuk bergadang di poskamling. Sampai larut malam, tak henti-hentinya aku membawa uang banyak, lalu pulang dengan kekecewaan. Berjudi. Melempar dan mengocok kartu. Kalah. Semuanya sudah diketahui keluargaku.
Rasanya malu bila anakku yang sudah berseragam putih abu-abu ditanyai gurunya. “Bapak kamu kerjanya apa?” Anakku menjawab, “Di pabrik. Tapi kalau malam berjudi.”
Sudah puluhan kali aku mendapati anakku menangis di sudut kamarnya. Kutanya kenapa ia menangis, jawabannya, “Aku malu ditertawakan teman-temanku karena aku anak penjudi.”
Malu. Sangat malu.
Dengan dipecatnya aku, berarti segala urusan yang harus mengeluarkan uang harus berhenti. Aku bersyukur akhirnya bisa berhenti berjudi. Aku akan malu bila melihat keluargaku sedang menahan lapar, sedangkan aku menanggung kekalahan di poskamling.
Beruntung aku memiliki istri yang penyabar. Mungkin jika istriku bukan dia, aku sudah ditinggal pergi ke rumah orang tuanya. Dia rela mencari pekerjaan sambilan untuk mencukupi kebutuhan, bahkan untuk sebulan ini dia lah yang menjadi tulang punggung keluarga.
Menjadi seorang suami sekaligus ayah, aku layak mendapat rapor merah.
Latar pendidikan yang rendah membuatku minder untuk mencari pekerjaan. Untuk sekarang ini, minimal pendidikan terakhir untuk mendapat perkerjaan adalah SMA sederajat. Aku hanyalah tamatan SD. Andai saja dulu orang tuaku memiliki uang untuk menyekolahkanku, aku ingin melanjutkan hingga bangku kuliah. Sayang sekali, uang penjualan sawah orang tuaku telah digunakan membayar hutang-hutang kakakku.
Aku bingung dari mana keluargaku bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup. Bisa saja sebenarnya bekerja serabutan, tapi belum cukup untuk membayar biaya sekolah ketiga anakku. Beginilah aku, lelaki sarungan yang sedang bingung bagaimana caranya melanjutkan hidup.
Malam hari yang biasanya diisi oleh tawa hangat keluarga, berubah jadi malam perenungan. Masing-masing orang di rumah merenung bagaimana caranya memperbaiki kualitas hidup. Istriku berkata, jangan dibawa pusing, Pak. Lebih baik dibawa senang dan diambil hikmahnya.
Aku melihat anak sulungku sedang belajar. Setahun lagi dia akan mengikuti Ujian Nasional. Hanya semangat dan motivasi yang bisa membuatnya mengubah nasib keluarga ini. “Belajar yang rajin, Nak. Jangan kayak Bapak, yang nasibnya nggak seberuntung kamu. Nggak bisa sekolah, masa tuanya luntang-lantung. Kalau urusan pendidikan, Bapak akan dukung kamu. Terserah kamu mau jadi apa, yang jelas kamu harus jadi orang yang berguna dan bisa membanggakan orang tua kamu. Kamu nggak usah mikirin gimana susahnya keluarga kita, fokus aja ke belajar.”
Aku mengusap kepalanya sambil menahan air mata. Harapanku ada pada anak-anakku.
Aku mengambil koran di meja kemudian membacanya. Aku lihat tanggal terbitnya, ah, ini koran sebulan yang lalu. Mungkin itu terakhir kalinya aku membeli koran, dan itu terakhir kalinya aku pulang kerja.
Karena, sebulan yang lalu aku dipecat.
Pulang ke rumah dengan langkah gontai, menemui penjual koran langganan. “Mas, ini mungkin terakhir kalinya saya beli koran di tempat, Mas.”
“Memang kenapa, Pak?” tanya penjual koran kepadaku.
“Nggak papa. Mungkin saya akan beli di tempat lain atau membaca berita online. Ini, kan, era digital. Hehehe,” kataku berdalih. Padahal aku samasekali nggak punya handphone.
Aku menyeruput kopi yang mulai mendingin. Ah, rasanya terlalu pahit. Sejak dipecat dari pabrik tempatku berkerja, otomatis kopi yang aku minum terasa pahit. Wajarlah, untuk membeli gula butuh banyak pertimbangan. Lebih baik uangnya dibelikan sebungkus nasi. Tapi tak apa, kopi ini adalah sisa dari persediaan tiga bulan. Memang, aku selalu membeli kopi untuk stok tiga bulan. Biar nggak bolak-balik ke pasar.
Merenung. Mengapa semua terjadi secara mendadak. Di saat keluargaku dalam keadaan baik-baik saja, kenapa pemecatan itu bisa datang? Apakah ini semua adalah balasan dari kebiasaan burukku selama lima tahun terakhir?
Entahlah, tapi aku merasa ini teguran dari Tuhan.
Lima tahun lalu adalah kali pertama aku keluar malam untuk bergadang di poskamling. Sampai larut malam, tak henti-hentinya aku membawa uang banyak, lalu pulang dengan kekecewaan. Berjudi. Melempar dan mengocok kartu. Kalah. Semuanya sudah diketahui keluargaku.
Rasanya malu bila anakku yang sudah berseragam putih abu-abu ditanyai gurunya. “Bapak kamu kerjanya apa?” Anakku menjawab, “Di pabrik. Tapi kalau malam berjudi.”
Sudah puluhan kali aku mendapati anakku menangis di sudut kamarnya. Kutanya kenapa ia menangis, jawabannya, “Aku malu ditertawakan teman-temanku karena aku anak penjudi.”
Malu. Sangat malu.
Dengan dipecatnya aku, berarti segala urusan yang harus mengeluarkan uang harus berhenti. Aku bersyukur akhirnya bisa berhenti berjudi. Aku akan malu bila melihat keluargaku sedang menahan lapar, sedangkan aku menanggung kekalahan di poskamling.
Beruntung aku memiliki istri yang penyabar. Mungkin jika istriku bukan dia, aku sudah ditinggal pergi ke rumah orang tuanya. Dia rela mencari pekerjaan sambilan untuk mencukupi kebutuhan, bahkan untuk sebulan ini dia lah yang menjadi tulang punggung keluarga.
Menjadi seorang suami sekaligus ayah, aku layak mendapat rapor merah.
Latar pendidikan yang rendah membuatku minder untuk mencari pekerjaan. Untuk sekarang ini, minimal pendidikan terakhir untuk mendapat perkerjaan adalah SMA sederajat. Aku hanyalah tamatan SD. Andai saja dulu orang tuaku memiliki uang untuk menyekolahkanku, aku ingin melanjutkan hingga bangku kuliah. Sayang sekali, uang penjualan sawah orang tuaku telah digunakan membayar hutang-hutang kakakku.
Aku bingung dari mana keluargaku bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup. Bisa saja sebenarnya bekerja serabutan, tapi belum cukup untuk membayar biaya sekolah ketiga anakku. Beginilah aku, lelaki sarungan yang sedang bingung bagaimana caranya melanjutkan hidup.
Malam hari yang biasanya diisi oleh tawa hangat keluarga, berubah jadi malam perenungan. Masing-masing orang di rumah merenung bagaimana caranya memperbaiki kualitas hidup. Istriku berkata, jangan dibawa pusing, Pak. Lebih baik dibawa senang dan diambil hikmahnya.
Aku melihat anak sulungku sedang belajar. Setahun lagi dia akan mengikuti Ujian Nasional. Hanya semangat dan motivasi yang bisa membuatnya mengubah nasib keluarga ini. “Belajar yang rajin, Nak. Jangan kayak Bapak, yang nasibnya nggak seberuntung kamu. Nggak bisa sekolah, masa tuanya luntang-lantung. Kalau urusan pendidikan, Bapak akan dukung kamu. Terserah kamu mau jadi apa, yang jelas kamu harus jadi orang yang berguna dan bisa membanggakan orang tua kamu. Kamu nggak usah mikirin gimana susahnya keluarga kita, fokus aja ke belajar.”
Aku mengusap kepalanya sambil menahan air mata. Harapanku ada pada anak-anakku.


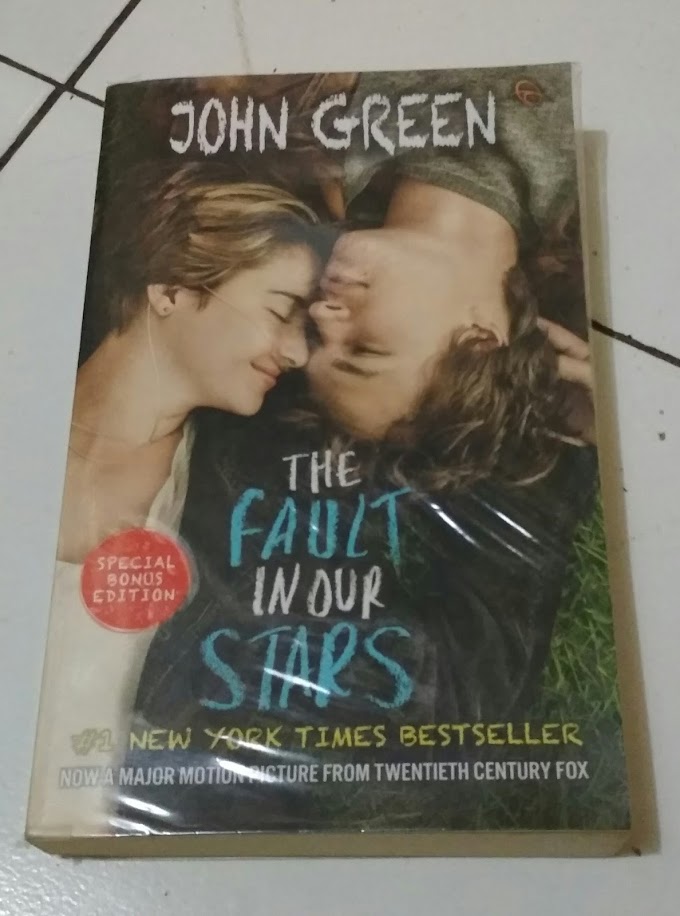




15 Comments
Wah robby ternyata udah anak
ReplyDeleteEngga sya duga loh sesudahnya
Iya, bang. Semoga cepet nyusul ya. :))
Delete:') Kamu emang jago bikin fiksi yang mencabik-cabik hati kayak Leonardo Dicaprio dicabik-cabik sama beruang grizzly. Buat si anak, tetaplah jadi anak yang berbakti. Yang walaupun malu sama kekhilafan Bapaknya sebelum dipecat, tapi tetap kelihatannya menghormati sang Bapak. Buat si istri, tetaplah menjadi istri yang berbakti, yang sabar kayak gitu. Ah. Cedih kalau udah baca fiksi tentang keluarga gini, Rob :'D
ReplyDeleteMakasih, kakak Icha~ Doanya diamini aja deh. :)
DeleteKeren, Rob. Satir banget nih. Tapi ada typo di bagian akhir..
ReplyDeleteMakasih Rahul atas koreksinya~
DeleteRobb.. Tumben bikin fiksi yg mnyentuh hati bginih.. :'D
ReplyDeleteTapi, keren kok :D
Makasih, Kakak Lulu. Masih dalam proses belajar nulis fiksi.
DeleteTernyata bisa juga bikin cerita fiksi, kalo saya nyerah deh.... Hahahahaha.
ReplyDeleteBang Hendra juga pasti bisa, kok. Semua orang pasti bisa. :)
DeleteBetapa kebapakan sekali anak muda satu ini.
ReplyDeleteGak sia-sia kamu dianggap udah kuliah nak. :')
Aduh, dikira mahasiswa semester 4. :') Padahal masih SMA semester 4 (kelas 2 SMA).
DeleteIni ngena banget sih :' sumpah :')
ReplyDeleteAku bener-bener terbawa dalam tulisanmu, Rob :')
Menampar para orang tua yang memiliki masa lalu kelam, dan menusuk para anak muda yang akan menjadi bapak :')
Terbawa perasaan, bang? Nggak terbawa perasaan mantan, kan? Hehehe. Ehm, itu boleh juga kesimpulannya. Tapi serem banget ada tampar dan nusuknya. :D
DeleteHwalaaah, masih harus belajar lagi, bang. Biar makin mantep nulis fiksinya. Hehehe.
ReplyDeleteTerima kasih sudah membaca. Mari berbagi bersama di kolom komentar.
Emoji